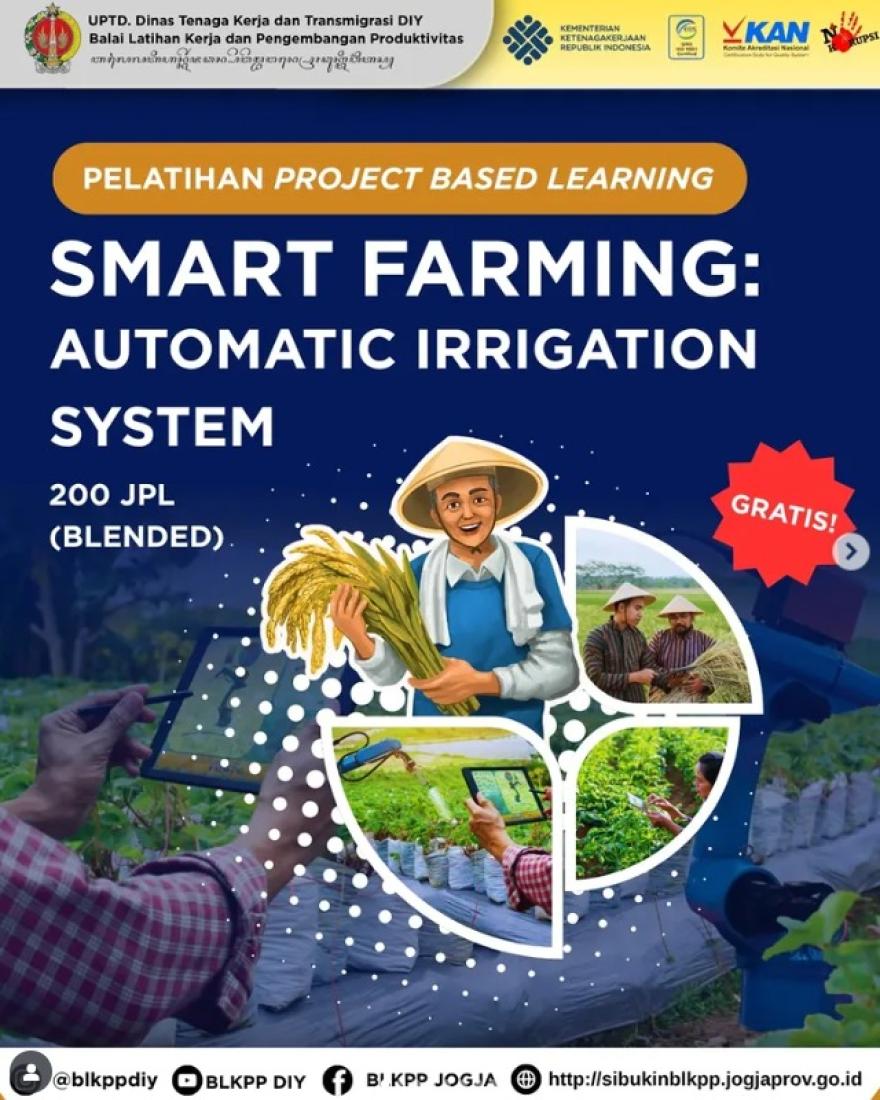Smart Farming Tanpa Tanah: Saatnya Hentikan Ilusi Pelatihan
Kata “smart” kini menjelma mantra baru pembangunan: smart farming, smart fishery, smart village, bahkan smart living. Semua terdengar modern dan futuristik, seolah menjadi jawaban atas kemiskinan struktural dan stagnasi produksi pangan. Namun, di balik euforia digitalisasi, muncul satu ironi besar—semua tampak cerdas hanya di atas kertas, bukan di atas tanah.
Di banyak tempat, pelatihan-pelatihan “smart” justru berakhir sebagai formalitas belaka. Rakyat datang, duduk, mendengarkan teori dari orang yang tak pernah menanam sebatang pun tanaman, lalu pulang dengan sertifikat. Ilusi kemajuan dibungkus rapi dengan slide presentasi dan laporan kegiatan. Padahal, yang dibutuhkan rakyat bukan pengetahuan yang dihafal, melainkan kemampuan yang menghasilkan telur, sayur, dan uang nyata.
1. Dari Smart Farming ke Smart Ilusi
Smart farming seharusnya tentang kecerdasan mengelola sumber daya alam dengan teknologi yang relevan. Namun di lapangan, kata “smart” justru jadi hiasan brosur proyek. Para pelatih datang dari kampus atau lembaga, berbicara tentang sensor tanah, Internet of Things (IoT), dan analisis data, padahal banyak di antara mereka tak pernah memegang cangkul atau memberi pakan ayam.
Pelatihan dilakukan di ruang ber-AC, jauh dari bau kandang dan lumpur sawah. Peserta mencatat dengan semangat, lalu kembali ke rumah tanpa tahu bagaimana menanam tomat di polibag. Sementara di sisi lain, biaya pelatihan bisa mencapai jutaan rupiah per orang—uang yang sebenarnya cukup untuk membeli sepuluh ekor ayam petelur dan bibit sayuran produktif.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa kata “smart” sering kali hanya menutupi realitas bahwa sistem pembangunan kita masih buta terhadap akar permasalahan: minimnya produksi nyata dan kemandirian pangan keluarga.
2. Sertifikat Tak Bisa Dimakan
Ironinya, banyak program pemerintah berakhir pada selembar kertas bernama sertifikat. Dokumen itu menjadi simbol partisipasi, bukan simbol kemampuan. Rakyat memang merasa “ikut program”, tapi tidak punya alat untuk memproduksi.
Di desa, ibu-ibu peserta pelatihan pulang membawa sertifikat “pelatihan hidroponik” tanpa satupun peralatan untuk menanam. Petani menerima sertifikat “digitalisasi pertanian” tanpa sinyal internet di desanya. Pelatihan berhenti di foto dokumentasi, sementara perut rakyat tetap kosong.
Bandingkan dengan ide “Bantuan Sosial Produktif Smart Protein” yang sederhana tapi konkret: sepuluh ayam petelur, bibit sayuran untuk lahan 20 meter persegi, dua bibit kelapa pendek, dan panduan video perawatan. Total biaya hanya Rp 850.000–Rp 1 juta per keluarga—lebih murah dari satu kali pelatihan.
Dari bantuan nyata itu, setiap keluarga bisa menghasilkan protein setiap hari, menambah pendapatan, dan menciptakan kemandirian pangan. Sertifikat bisa dipajang di dinding, tapi telur di dapur bisa menyelamatkan anak dari gizi buruk.
Baca juga : Mengenal NPU di Laptop Snapdragon: Otak AI yang Bikin Laptop Makin “Pintar”
3. Dana yang Salah Arah
Masalah utama pembangunan bukan kurang dana, tapi dana yang salah arah. Jutaan rupiah dihabiskan untuk seminar, banner, dan akomodasi pelatih, tapi tidak menyentuh kebutuhan dasar petani: alat produksi dan pendampingan nyata.
Satu kali pelatihan bisa menghabiskan Rp 3 juta per orang. Jika dana itu dialihkan ke bantuan produktif, satu desa kecil sudah bisa menjadi pusat pangan mandiri. Pemerintah sering lupa bahwa kemajuan tidak datang dari gedung pelatihan, tetapi dari kandang ayam dan lahan yang diolah.
Setiap rupiah yang tak menghasilkan produksi adalah angka kosong. Ia mungkin memperindah laporan keuangan, tapi tak pernah memberi makna pada piring rakyat.
4. Ekonomi Tumbuh dari Produksi, Bukan Pelatihan
Dalam teori ekonomi, Slow Growth Model menjelaskan bahwa penambahan modal tanpa peningkatan produktivitas hanyalah penambahan angka, bukan kemajuan. Artinya, memberi dana tanpa memastikan hasil produksi tidak akan mengubah nasib rakyat.
Namun ketika modal kecil diarahkan pada kegiatan berulang yang meningkatkan efisiensi—seperti beternak ayam atau menanam sayur dengan teknik sederhana—produktivitas (A) akan naik, ICOR turun, dan pertumbuhan ekonomi menjadi nyata.
Sementara menurut Paul Romer, pertumbuhan modern lahir dari penyebaran ide dan pengetahuan. Tapi penyebaran ide itu tidak terjadi lewat seminar, melainkan lewat tindakan nyata yang bisa ditiru. Ketika satu keluarga sukses beternak ayam, tetangga akan meniru. Lalu satu desa belajar dari desa lain. Ide berkembang secara eksponensial.
Dengan kata lain, pengetahuan hanya berguna ketika ia tumbuh di tangan, bukan di kepala saja.
5. Rakyat Bukan Objek Pelatihan
Selama ini, rakyat diposisikan sebagai objek pelatihan. Mereka mendengar, mencatat, berfoto bersama pejabat, lalu dilupakan. Jarang sekali mereka dijadikan subjek aktif yang mengelola hasil, belajar dari kegagalan, dan memproduksi sendiri.
Sikap ini membuat masyarakat bergantung terus pada program berikutnya. Padahal, yang dibutuhkan bukan bimbingan terus-menerus, melainkan kesempatan untuk mempraktikkan langsung. Rakyat tidak butuh “pencerahan”, mereka butuh akses alat, bibit, dan pasar.
Bangsa ini tidak butuh lebih banyak laporan kegiatan, tapi lebih banyak telur, sayur, dan hasil bumi yang bisa dikonsumsi dan dijual. Kedaulatan pangan dimulai dari tangan rakyat, bukan dari presentasi PowerPoint.
6. Ilusi Modernitas di Ruang Ber-AC
Teknologi sering dianggap solusi universal. Tapi tanpa konteks lokal, teknologi hanya menjadi simbol modernitas semu. Di banyak pelatihan, istilah seperti “IoT”, “big data”, atau “blockchain agriculture” sering digunakan, tapi penerapannya tak pernah sampai ke sawah.
Padahal, teknologi tidak harus rumit. Dalam konteks rakyat desa, kecerdasan bisa sesederhana menggunakan ember bekas untuk hidroponik, atau mengatur jadwal pakan ayam dengan alarm HP. Yang penting bukan seberapa “canggih” sistemnya, tapi seberapa relevan dengan kehidupan sehari-hari.
Mereka yang tinggal di kota sering lupa: kecerdasan sejati bukanlah tentang digitalisasi, melainkan adaptasi. Cerdas bukan berarti berteknologi tinggi, tapi mampu bertahan dan berproduksi dengan sumber daya yang ada.
7. Dari Teori ke Lumpur: Membangun Mitra, Bukan Murid
Petani dan nelayan tidak butuh teori dari ruang ber-AC. Mereka butuh mitra yang mau turun ke lumpur, bukan mentor yang hanya memberi arahan. Ilmu pertanian tidak bisa diserap dari layar presentasi, tapi dari pengalaman langsung di lahan dan kandang.
Jika ingin menciptakan perubahan, sistem pelatihan harus diubah menjadi sistem pendampingan. Pendamping harus ikut bekerja, bukan hanya memberi tugas. Belajar harus dilakukan di tempat produksi, bukan di ruang rapat.
Ketika rakyat merasa memiliki prosesnya, maka semangat belajar akan tumbuh alami. Itulah cara pengetahuan tumbuh menjadi keterampilan.
8. Dari Pelatihan ke Produksi: Program yang Menghidupkan
Setiap program yang tidak menghasilkan produksi pada akhirnya akan mati bersama anggarannya. Karena itu, jika pemerintah ingin meninggalkan warisan yang benar-benar hidup, arah kebijakan harus bergeser dari pelatihan menuju produksi.
Bayangkan jika setiap rumah di desa memiliki dua ekor sapi kecil, satu kebun sayur, dan satu kolam ikan. Setiap keluarga akan memiliki sumber gizi, pendapatan tambahan, dan kebanggaan.
Program semacam ini tidak hanya memberi hasil ekonomi, tapi juga mengembalikan harga diri rakyat sebagai produsen pangan.
Itulah makna sejati dari kedaulatan: ketika rakyat bisa makan dari tangannya sendiri.
9. Mengubah Paradigma: Dari Sertifikat ke Kemampuan
Kemakmuran tidak datang dari selembar sertifikat. Ia lahir dari kemampuan nyata yang menghidupi keluarga.
Setiap telur yang menetas, setiap sayur yang tumbuh, dan setiap panen yang dijual adalah bukti bahwa perubahan dimulai dari tindakan kecil.
Pemerintah perlu mulai melihat pembangunan bukan sebagai proyek citra, tapi sebagai investasi pada kemampuan rakyat. Pelatihan harus menjadi alat, bukan tujuan.
Hanya dengan begitu, bangsa ini bisa beranjak dari budaya laporan menuju budaya hasil.
10. Kesimpulan: Sejarah Hanya Mengingat yang Menghidupi
Sejarah tidak akan mengingat seminar, tapi mengingat siapa yang memberi rakyat kemampuan untuk hidup.
Bangsa ini tidak butuh lebih banyak pelatihan tentang cara bercocok tanam di PowerPoint, tapi lebih banyak kandang dan kebun di setiap rumah. Tidak butuh lebih banyak kata “smart”, tapi lebih banyak tindakan cerdas di lapangan.
Ketika program pembangunan berhenti mengajarkan teori dan mulai menumbuhkan ayam di kandang rakyat, saat itulah bangsa ini benar-benar bergerak menuju kemandirian.
Karena kemakmuran bukanlah hasil dari sistem yang terlihat canggih, melainkan hasil dari tangan-tangan yang bekerja dan menghasilkan kehidupan.